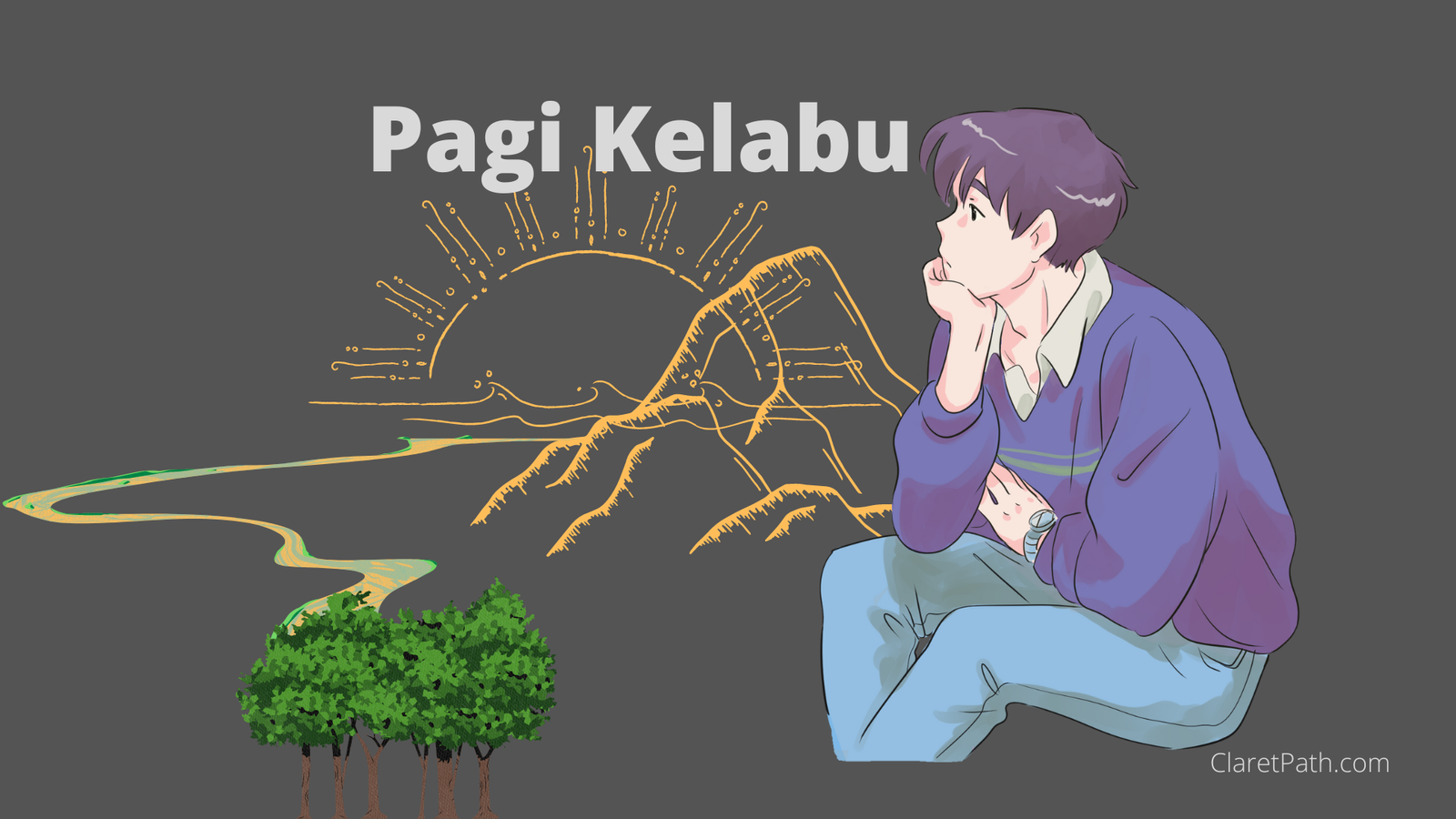ClaretPath.com – Pagi itu kelabu. Kuberharap jadi prabu. Tapi nyatanya aku terdampar jadi babu. Padahal sejak semalam hasrat memeluk gunung telah tersimpan dalam kalbu. Hmmm, selalu sial nasibku setiap hari rabu.
Jalanan licin. Sudah sejak subuh hujan lebat. Ibu memang sudah memperingatkanku untuk tak keluar dari rumah. Apalagi ke puncak, ibu sama sekali tak mengizinkan. Tapi, sudah lama kunanti momen ini. Karena itu, tak kuhiraukan kata-kata ibuku.
“Aduh sakiiit!” jeritku lirih menahan rasa perih di lututku.
Rasanya ingin menangis sekeras-kerasnya. Ingin kumeraung memecahkan dinding klinik yang terbuat dari tripleks bertirai bambu itu. Bukan hanya karena perih di lutut, melainkan juga karena kecewa tak ikut ke puncak dalam program hiking desa kali ini. Namun, apalah daya. Bukan tak boleh, tapi mana mungkin? Aku malu kedapatan menjerit apalagi menangis di hadapan perawat mungil pemilik senyum manis yang baru bertugas di desaku seminggu yang lalu. Meski sakit, rasa itu kutahan, lalu kubenamkan untuk kunikmati sendiri.
Aku terdiam, lalu membisu. Tak bisa kurangkai lagi huruf-huruf untuk jadi kata pada bibirku. Kupendam dalam-dalam mengendap dalam relung kalbuku. Aku hanya bisa membatin. Apa gerangan nasibku setiap hari rabu? Mengapa selalu kelabu?
Masih di bilik kecil klinik desaku ini aku bergulat. Sakit lututku nyut-nyut seiring gerak pompa jantungku. Bengkaknya mulai menjalar ke seluruh permukaan tempurung lutut. Aku tak habis pikir, mengapa semuanya bisa terjadi?
Seandainya aku dengarkan larangan ibuku, pasti aku tak sial seperti ini. Seandainya aku tak terburu-buru, pasti aku tak tergelincir dan jatuh. Seandainya aku tak kaget saat jatuh, pasti aku bisa mengurangi risiko buruk seperti ini. Seandainya tempurung lututku tak pecah dan aku masih bisa berdiri, pasti aku segera ke klinik ini untuk dapatkan perawatan lebih dini.
Ah…seandainya, ….pasti…., seandainya …., pasti…, cuma itu yang aku bisa. Kuberharap dalam khayalku. Ingin mengubah nasi yang telah menjadi bubur.
***
Perawat mungil itu masih berdiri di bilik depan sana. Aku bisa melihatnya dengan jelas karena bilik itu terletak satu garis lurus dari tempat aku berbaring. Maklum klinik di desa, bilik-biliknya hanya dibatasi dengan sekat tirai bambu yang celahnya lebar seperti ventilasi. Dulu dibuat seadanya oleh seorang calon bupati untuk meyakinkan orang-orang di desaku supaya memenangkannya dalam pilkada. Dasar politisi murahan, hanya mau bantu orang saat ada maunya. Sudah begitu, bantunya setengah-setengah pula.
Sudah pukul 06.00 pagi sekarang. Seharusnya, aku sudah di titik kumpul. Tapi, nyatanya aku masih di sini. Bergulat dengan sakit ini. Memar di kaki, biru kemerahan. Sepertinya patah tulang lututku.
Parah hidupku. Hasrat hati ingin senang-senang. Eh, malah terbaring lemas di klinik ini. Aku sudah seperti orang lumpuh, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Jangankan berjalan ke titik kumpul pagi ini, berdiri saja tak bisa. Apalagi sampai ke puncak, itu mustahil.
Kini kuharap mukjizat terjadi. Jika itu berlebihan, kuharap semua ini cuma mimpi. Tapi sayang, ini bukan mimpi. Karena itu, lebih mungkin jika kuharapkan mukjizat saja. Berharap tiba-tiba ada cahaya dari langit memancar ke lututku dan seketika sembuh luka dan bengkaknya.
***
Tiba-tiba….
Kulihat seorang perempuan tua dari kejauhan. Lagi-lagi mohon dimaklumi, klinik ini seadanya sehingga orang dari dalamnya bisa menangkap dengan jelas orang-orang yang berada di luar. Semakin mendekat, semakin kukenali perempuan baya itu.
Ternyata dia ibuku. Dia yang melarangku untuk keluar rumah kemarin. Dialah yang tak mengizinkanku pergi ke puncak. Dia tak ingin terjadi sesuatu yang buruk padaku. Dia paham benar, hiking pada waktu hujan itu tidak mudah. Dia sudah menjelaskan padaku panjang lebar alasan larangannya padaku untuk ke puncak. Tapi, aku tak menghiraukan semuanya. Padahal dia berkata demikian karena pernah mengalami hal buruk ketika dulu pernah hiking pada waktu hujan.
Ibuku masuk ke bilik tempat aku berbaring. Di sampingnya berdiri perawat, si pemilik senyum manis itu. Aku hanya diam menatap ibuku. Sesekali ekor mataku melirik perawat itu. Berharap si pemilik senyum manis itu membelaku jika ibuku ingin memarahiku. Aku menanti apa yang akan keluar dari mulut ibuku.
Kami bertiga hening. Ibu dan aku saling menatap sayu. Perawat itu menyaksikan adegan itu terharu. Ternyata ibuku tak memarahiku. Perlahan ibuku mendekat, lalu menyentuh lututku dengan manja.
“Kalau mama larang, kamu harus dengarkan ya, Nak!” katanya manja sambil mengelus kepalaku. Tangan kirinya seolah menjamah lututku, sementara tangan kanannya tiada henti mengelus manja kepalaku.
“Untung tadi ditemukan orang-orang yang mau pergi ke kebun, Bu! Dia jatuh dalam parit persis di sebelah tanjakan terjal itu” kata perawat itu mengusik keheningan dan kehangatan di antara ibu dan aku. “Tapi syukurlah, sekarang sudah tertangani. Tidak akan lama kok. Itu pun kalau dia taat dengarkan pantangan-pantangan yang kami berikan nanti.”
Perawat itu seakan tahu kalau semua sakit ini aku alami akibat tidak mau mendengarkan larangan ibuku semalam. Aku terdiam. Juga ibu dan perawat itu tanpa kata lagi terucap. Kami hening.
***
Sebenarnya, bukannya aku tak taat dengarkan kata-kata ibuku. Tapi aku sudah terlanjur berjanji pada teman-teman sebayaku untuk ikut hiking kali ini. Apalagi sudah beberapa kali program hiking pengurus karang taruna desa aku tak pernah berpartisipasi. Padahal aku sekretaris karang taruna di desaku.
Cuma itu niatku. Aku hanya ingin memenuhi janji bahwa hiking kali ini aku pasti ikut. Hatiku memang tak ingin hiking. Tapi aku mau tunjukan pada teman-teman bahwa aku sekretaris yang bertanggung jawab. Aku ingin buktikan bahwa aku pasti melakukan apa yang telah kujanjikan. Aku tak ingin dianggap tak bertanggung jawab dengan jabatan yang mereka percayakan padaku. Tapi, aku tak bisa memungkiri hati kecilku.
Aku setuju dengan kata-kata ibuku. Hatiku mengiyakan larangannya. Tapi gengsiku mengiyakan tantangan teman sebayaku. Apalagi sudah berulang kali mereka mengkritikku sebagai sekretaris yang cuma nama doang. Hanya itu motif aku ingin ikut hiking kali ini. Aku ingin buktikan diri sebagai sekretaris yang komitmen pada janji. Tapi, celaka nan nahas pagi ini kembalikanku pada gulat dengan diri sendiri.
Aku tak paham, apakah aku harus ikuti kata ibu atau kata teman-temanku. Aku harus mendengarkan yang mana, kritik pedas teman sebayaku atau kata hatiku. Aku seharusnya ikuti bisikan relung kalbuku atau hasutan gengsi biar kelihatan cool sebagai seorang sekretaris.
***
Mata ibuku sayu. Dia tak mampu melihatku menderita. Sejak duduk di samping tempat tidur aku berbaring, tangannya tiada henti mengusap kepalaku manja. Sentuhannya membuatku nyaman. Tapi di saat yang sama, rasanya aku tak layak menerima sentuhan hangat nan tulus itu. Aku sangat merasa bersalah pada ibuku. Seharusnya aku mendengarkan dia.
Kini kusadar siapa yang sesungguhnya mencintaiku. Di saat aku menderita, ternyata hanya ibuku yang selalu menemaniku. Bukan baru kali ini! Sudah berulang kali, bahkan sejak aku bayi. Hanya ibuku tempat aku bersandar. Apalagi ayaku sudah pergi meninggalkan kami sewaktu aku bayi. Cinta ibuku sungguh tiada duanya.
Hatiku terharu. Memang pagi ini kelabu. Harapku jadi prabu terlempar jadi babu. Tapi semuanya sekarang tiada artinya lagi. Telah kutemukan kembali seberkas sinar yang mencerahkan. Ketulusan cinta ibu membuat aku berharap lagi. Dialah mukjizatku di kala setiap aku dalam keadaan terpuruk.
Aku berjanji: aku akan selalu mendengarkan kata-katanya! Terima kasih ibuku tercinta!
(tm)
Pecinta Literasi